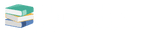Akhir-akhir ini, perbincangan di dunia maya kembali ramai dengan pandangan sebagian kalangan Salafi yang menyatakan bahwa berdzikir dengan menggunakan tasbih adalah sebuah bid’ah dalam Islam. Mereka berargumen bahwa tasbih adalah inovasi baru yang tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW.
Untuk mendukung pandangan ini, mereka merujuk kepada fatwa seorang ulama yang dikenal dengan gelar ‘Muhadditsu-Syam’ (ahli hadis dari Syam), dan bahkan sebagian di antara mereka menyebutnya ‘Muhadditsud-Dunya’ (ahli hadis dunia). Ulama tersebut adalah Muhammad bin al-Haj Nuh bin Nijati bin Ādam al-Isyqudri al-Albāny, atau lebih dikenal sebagai al-Albani.
Namun, pada kesempatan ini, kami tidak berfokus untuk memperdebatkan apakah penggunaan tasbih merupakan perkara bid’ah atau tidak, karena sudah banyak ulama yang membahas topik ini secara mendalam. Sebaliknya, kami tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai kredibilitas al-Albani terkait gelar ‘al-Muhaddits’ (ahli hadis). Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami kriteria ulama yang layak diberi gelar tersebut menurut pandangan para ahli.
Dalam hal ini, Imam as-Suyuthi dalam kitab Tadrib ar-Rawi mengutip perkataan Syekh Fathu ad-Din, “Ahli hadis (al-Muhaddits) di masa kami adalah orang yang dihabiskan waktunya dengan hadis baik secara riwayat atau ilmu mushthalah (dirayah), dan orang tersebut mengetahui beberapa perawi hadis dan riwayat di masanya, serta menonjol sehingga dikenal daya hafalannya dan daya akurasinya. Jika ia memiliki pengetahuan yang lebih luas sehingga mengetahui para guru, dan para maha guru dari berbagai tingkatan, sekira yang ia ketahui dari setiap jenjang tingkatan lebih banyak daripada yang tidak diketahui, maka orang tersebut adalah al-Hafidz”.[1]
Dari sini, dapat kita tarik garis merah bahwa seorang dapat dianggap sebagai ahli hadis apabila ia telah mampu untuk menguasai hadis baik dari segi riwayat maupun dirayah, serta mengetahui beberapa rawi hadis dan riwayat di masanya, sehingga daya hafalan dan akurasinya dikenal oleh banyak orang. Pastinya, akan terbesit di benak pembaca, “Apakah Albani memenuhi kriteria-kriteria tersebut?”.
Untuk menjawab pertanyaan itu, kami akan mengutip kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah al-Harari tentang Albani dalam kitabnya yang bertajuk Tabyinu Dhalalati Albani,
وقد ذكر لنا أن رجلا من المحامين قال له : أنت محدث؟ قال: نعم، قال: تروي لـنـا عـشـرة أحاديث بأسانيدها ، قال : أنا لست محدث حفظ بل محدث كتاب، فقال الرجل : وأنا أستطيع أن أحدث من كتاب، فأسكته.
Diceritakan bahwa ada seseorang dari Mahami yang bertanya kepada Syekh Albani: “Apakah anda ahli hadis (Muhaddits)?” Syekh Albani menjawab: “Ya!” Ia bertanya: “Tolong riwayatkan 10 hadis kepada saya beserta sanadnya!” Syekh Albani menjawab: “Saya bukan ahli hadis penghafal, saya ahli hadis kitab.” Orang tadi berkata: “Saya juga bisa kalau menyampaikan hadis ada kitabnya.” Lalu Syaikh Albani terdiam.[2]
Begitu juga, kisah yang dikutip oleh Abdullah bin Muhammad asy-Syamrani tentang Albani,
عُرِفَ الشَّيْخُ اْلأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللهُ بِقِلَّةِ شُيُوْخِهِ وَبِقِلَّةِ إِجَازَاتِهِ . فَكَيْفَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُلِّمَّ بِالْعُلُوْمِ وَلاَ سِيَّمَا عِلْمِ الْحَدِيْثِ وَعِلْمِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ عَلَى صُعُوْبَتِهِ ؟
“Syekh Albani dikenal dengan sedikitnya guru dan minimnya ijazah dalam hadis. Maka bagaimana ia mampu memperdalam ilmu-ilmu, apalagi ilmu hadis dan ilmu tentang metode memberi penilaian cacat dan adil yang sangat sulit?”.[3]
Dari kisah yang dikutip oleh Syekh Abdullah al-Harari dan Abdullah asy-Syamrani, setidaknya kita menemukan titik cerah bahwa Albani adalah seorang yang mempelajari hadis melalui satu kitab ke kitab yang lain, dan ia mengaku bahwa dirinya bukanlah orang yang menghafalkan hadis-hadis yang ia dalami sebagai ‘Al-Muhaddits’.
Di sisi lain, ulama telah memberi rambu-rambu merah mengenai hadis yang diambil dari orang-orang yang belajar secara otodidak. Orang yang belajar secara otodidak dalam Mushthalah al-Hadis disebut dengan “shahafi”. Adapun terkait kredibilitas rawi hadis yang dianggap shahafi, Imam ad-Darimi berkata,
يَقُوْلُ الدَّارِمِي مَا كَتَبْتُ حَدِيْثًا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ صَحَفِيٍّ
“Ad-Darimi (ahli hadis) berkata: Saya tidak menulis hadis (tapi menghafalnya). Ia juga berkata: Jangan mempelajari ilmu dari orang yang otodidak”[4]
Syekh Syuaib al-Arnauth menjelaskan lebih detail tentang ‘shahafi’, Shahafi adalah orang yang mengambil ilmu dari kitab, bukan dari guru. Menurutnya, orang seperti ini tidak diperhitungkan ilmunya, sebab akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu, para ulama tidak memperhitungkan ilmu seseorang yang diambil dari buku, yang tidak melalui jalur riwayat, pembelajaran dan pembahasan.
Sebagai contoh rawi-rawi yang dianggap shahafi adalah Ibnu Hubaib. Ulama menyatakan bahwa riwayatnya tidak bisa diterima sebab ia dianggap shahafi. Dalam Siyar A’lam an-Nubala’ dijelaskan,
وممن ضعف ابن حبيب أبو محمد بن حزم، ولا ريب أنه كان صحفيا
“Diantara yang menilai dhaif Ibnu Hubaib adalah Abu Muhammad bin Hazam. Dan tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Hubaib adalah otodidak”.[5]
Hal ini tidak lain dikarenakan seorang ahli hadis diharuskan untuk mempelajari hadisnya melalui para guru agar tidak terjerumus ke dalam jurang kesalahan dan kekeliruan dan tidak seyogyanya ia mendapatkan hadis hanya melalui kitab dan lembaran saja. Oleh karena itu ulama salaf mengatakan:
لا تأخذ القرآن من مصحفيٍّ، ولا الحديث من صحفيٍّ
“Jangan mengambil al-Quran dari orang yang membaca mushaf (tanpa guru), dan jangan mengambil hadis dari orang yang membaca kitab dan lembaran (tanpa guru)”.[6]
Dari uraian di atas, pembaca dapat menemukan titik cerah, apakah kredibilitas Syekh Albani memang layak disematkan sebagai al-Muhaddits (ahli hadis) atau tidak? Apakah Syekh Albani layak dijuluki ‘Muhaddits ad-Dunya’ atau tidak? Mari berpikir dengan nalar yang sehat.
Penulis merupakan Mahasantri semester 1 (Angkatan Amatsil)
Editor: Vigar Ramadhan Dano M. D.
[1]Tadribur-Rawi Syarah Taqrib 1/11
[2] Tabyin Dlalalat Albani 6
[3] Tsabat Muallafat al-Albani’ 7
[4] Siyar A’lam an-Nubala, 8/34
[5] Siyar A’lam an-Nubala’ 12/106
[6] Taisir Mushtalahil-Hadis, 213